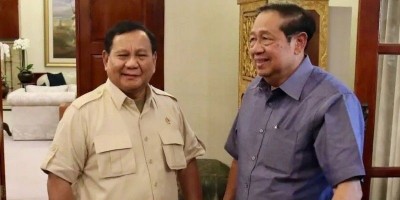Oleh: Irdam Imran, Pengamat Politik Lokal dan Studi Elite
RATUSAN ribu dislike terhadap video monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tentang bonus demografi bukan sekadar respons digital. Ia adalah ekspresi kolektif dari kekecewaan rakyat terhadap kualitas kepemimpinan nasional pasca-Pilpres 2024. Bukan isi video itu yang menyulut amarah, melainkan siapa yang menyampaikannya, dan dari mana legitimasi itu berasal.
Monolog itu, betapapun rapi penyajiannya, terasa artifisial. Publik kita, yang telah matang secara politik, tahu membedakan mana pemimpin yang bicara dari kedalaman pemahaman, dan mana yang hanya mengucapkan naskah dari tim komunikasi. Dalam video itu, publik tidak menemukan substansi, hanya simbol—dan simbol itu gagal meyakinkan.
Sebagai pengamat studi elite dan dinamika politik lokal, saya mencatat bahwa saat ini Indonesia berada di fase kritis dalam sejarah demokrasinya. Krisis bukan hanya soal kebijakan, tapi menyentuh hal paling mendasar: kepercayaan publik. Ketika posisi strategis seperti Wakil Presiden tidak lagi ditentukan oleh meritokrasi, melainkan oleh koneksi dan kekuasaan dinasti, maka runtuhlah harapan bahwa kualitas bisa tumbuh dalam sistem politik kita.
Pernyataan Prabowo Subianto—bahwa orang “bodoh, tidak suka baca” bisa menjadi wapres—mempertegas sinisme itu. Publik tak bisa tidak mengaitkan kalimat tersebut dengan sosok Gibran. Ketika pemimpin justru merayakan anti-intelektualisme, ketika kebodohan diberi tempat sebagai strategi politik, maka itu bukan hanya degradasi logika demokrasi, tetapi juga pengkhianatan terhadap cita-cita republik.
Bonus demografi, sejatinya, adalah peluang satu kali dalam sejarah bangsa. Jutaan generasi muda produktif akan menjadi aset atau bencana, tergantung pada kualitas perencanaan hari ini. Tapi bagaimana kita berharap pada kepemimpinan yang tak memahami dinamika struktural tenaga kerja, pendidikan, dan transformasi digital global?
Kita sedang berdiri di tepi jurang demografis. Jika tidak segera dibangun visi yang kuat, sistem pendidikan yang progresif, dan ekosistem lapangan kerja yang inklusif, maka bonus itu akan menjadi beban. Pengangguran massal, krisis sosial, dan frustrasi kolektif bisa membalik keuntungan itu menjadi ledakan ketidakstabilan.
Sayangnya, elit kita terlalu sibuk memoles citra dan mengamankan posisi. Tidak ada strategi besar yang terdengar. Tidak ada desain kebijakan yang terintegrasi. Tidak ada mimpi bersama yang dikomunikasikan secara jujur dan kredibel.
Respons publik atas video Gibran sejatinya adalah peringatan dini. Masyarakat, meski terlihat pasif, memiliki radar yang tajam terhadap ketulusan dan kapasitas. Tombol dislike mereka tekan bukan karena benci, tapi karena kecewa. Karena mereka tahu, bangsa ini pantas mendapatkan lebih.
Namun rasa kecewa itu, jika tidak diolah, bisa membeku menjadi apatisme. Dalam ruang-ruang sunyi diskusi politik, mulai terdengar suara: “Indonesia gelap, kabur saja dulu.” Ini berbahaya. Sebab jika masyarakat sipil menyerah, maka ruang demokrasi akan sepenuhnya dikuasai oleh elit yang tak peduli pada kualitas.
Justru di titik inilah masyarakat sipil harus bangkit. Kita tidak bisa berharap pada kekuasaan yang sudah kehilangan arah. Tapi kita bisa membangun kekuatan baru dari bawah: komunitas, gerakan akar rumput, pusat-pusat edukasi politik informal yang mengedepankan kesadaran kritis. Bukan untuk memberontak, tapi untuk menjaga agar republik tetap waras.
Demokrasi yang sehat lahir dari partisipasi. Jika hari ini kualitas kepemimpinan kita jatuh, maka itu juga karena publik dibiarkan menjadi penonton. Sudah saatnya kita menjadi pelaku: mendidik pemilih, membentuk opini publik, dan menghadirkan calon pemimpin yang lahir dari jalan panjang pengabdian dan pemikiran.
Indonesia tidak boleh kehilangan harapan hanya karena satu generasi elite gagal menunjukkan kualitasnya. Sejarah bangsa ini dibangun dari siklus jatuh dan bangun. Dan setiap kebangkitan selalu dimulai dari kesadaran rakyat biasa—bukan dari pidato, bukan dari monolog, tapi dari langkah kecil yang jujur.