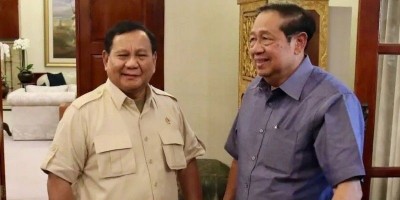Oleh: Edhy Aruman, Wartawan Senior dan Dosen Komunikasi
PATRICK Cockburn bukanlah orang asing dalam menghadapi kekacauan. Sebagai jurnalis perang untuk The Independent, ia telah menyaksikan kehancuran dari Baghdad hingga Kabul.
Ia terbiasa menavigasi bahaya, membaca situasi genting, dan melaporkan kebenaran dari medan konflik. Namun, tidak ada medan perang yang sebanding dengan satu krisis pribadi yang tiba-tiba menerpa hidupnya: sang putra, Henry.
Di tengah suara bom dan senapan, kabar dari rumah seolah mengguncang fondasi jiwanya lebih keras dari apa pun. "Henry masuk rumah sakit," kata istrinya. Kalimat itu menjadi titik awal dari perjalanan panjang dan menyakitkan untuk memahami sebuah dunia baru.
Sebuah dunia di mana realitas dan ilusi saling berbenturan, dan logika jurnalis tidak lagi bisa menjadi pegangan, Henry divonis menderita skizofrenia.
Sebagai ayah, Patrick merasa kalah. Tidak karena ia tak peduli, tapi karena ia tak tahu harus berbuat apa. Ia terbiasa pada fakta, data, dan strategi. Tapi bagaimana menghadapi suara-suara yang hanya Henry yang dengar? Bagaimana merespons ketika anaknya berlari keluar rumah sakit karena menganggap dirinya utusan spiritual?
Sebelum semua berubah, Henry adalah jiwa muda yang lembut dan penuh warna. Ia tumbuh sebagai anak yang cerdas, sangat mencintai alam, dan menunjukkan bakat luar biasa dalam seni. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam menggambar, berjalan di taman, atau merenung tentang puisi dan filsafat.
Patrick mengenangnya sebagai “anak yang damai dengan dunia,” seorang seniman muda yang lebih suka mengamati angin menyapu pepohonan ketimbang larut dalam hiruk-pikuk kehidupan remaja kebanyakan.
Ia belajar di sekolah seni dan dikenal sebagai pemuda yang idealis dan pemikir. Namun perlahan-lahan, kepekaannya yang halus terhadap dunia berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap.
Ia mulai menyampaikan gagasan-gagasan aneh tentang pesan dari pohon, dan tentang panggilan spiritual yang harus ia penuhi. Awalnya itu terdengar seperti eksentrik khas seniman muda. Tapi kemudian, semua itu berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan.
Pada suatu hari dingin di bulan Februari, suara-suara memanggil Henry untuk melangkah ke laut. Ia nyaris tenggelam. Bagi Henry, itu bukan tindakan nekat, tapi sebuah misi spiritual. “Aku merasa seperti aku sedang berada di dalam alam lain—sebuah dunia spiritual yang tak bisa dimengerti orang lain,” katanya lirih.
Bagi Patrick, itu adalah awal dari perpisahan yang sunyi—putranya masih hidup, tapi bukan lagi anak yang ia kenal.
Skizofrenia merenggut Henry seperti badai pelan yang tak bersuara. Ia kehilangan pijakan realitas, menolak obat, dan berkelana di jalanan karena merasa dirinya dipanggil oleh semesta.
Ia melukis, menulis, tapi sering tak bisa membedakan antara kanvas dan kenyataan. Dinding rumah sakit menjadi penjara sekaligus pelindung. Suara-suara menjadi musuh dan teman. Masa depan yang pernah terbentang kini berubah menjadi teka-teki tanpa petunjuk arah.
Ada kontras tajam antara dunia luar Patrick yang penuh logika dan kenyataan, dan dunia dalam Henry yang diliputi oleh kepercayaan magis dan ilusi yang membingungkan. Patrick berusaha menjembatani dua dunia itu dengan cinta dan kesabaran, meskipun ia sendiri tak selalu yakin apakah itu cukup.
Ia mencatat betapa pedihnya saat Henry memanggilnya “musuh”, hanya karena ia mendukung pengobatan yang dianggap Henry sebagai bentuk penindasan terhadap jiwanya yang bebas.
“Menjadi orang tua dari seseorang yang menderita skizofrenia berarti harus menerima kenyataan bahwa cinta saja tidak menyembuhkan. Tapi cinta adalah satu-satunya alasan kami terus bertahan,” ungkapnya.
Kisah ini dituangkan dengan jujur dan menyayat hati dalam "Henry’s Demons: Living with Schizophrenia, A Father and Son’s Story", sebuah memoar ganda yang sangat emosional dan mendalam, ditulis oleh Patrick Cockburn dan Henry Cockburn.
Di buku itu ada perjalanan hidup seorang pemuda dengan skizofrenia. Juga ada perjuangan keluarganya, terutama sang ayah, dalam memahami, menerima, dan membantu proses pemulihan anaknya.
Dengan gaya narasi yang bergantian antara Henry dan Patrick, pembaca dibawa menyelami dua dunia yang sangat berbeda: dunia seorang ayah yang mencoba merawat dengan nalar dan kasih, dan dunia seorang anak yang hidup dalam kabut realitas yang terdistorsi.
Dan seperti segala kisah tentang luka, kisah ini tidak berakhir dengan sembuh—tapi dengan harapan. Setelah bertahun-tahun menghilang, kabur, dan berjuang, Henry perlahan kembali. Ia kini tinggal sendiri di Herne Bay. Ia menulis lagi. Ia hidup, tidak dalam kemenangan, tapi dalam kedamaian kecil yang ia bangun sendiri.
Bagi Patrick, itu cukup. Bukan karena rasa sakit telah hilang, tapi karena kini, setiap pagi saat melihat Henry bangun, ia tahu: meski kabut itu belum sepenuhnya pergi, ada cahaya yang mulai menembus. Dan itu, baginya, adalah kemenangan paling agung.