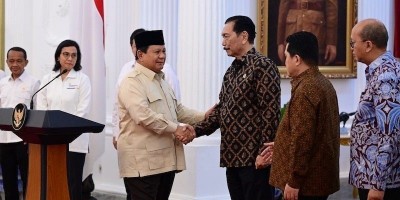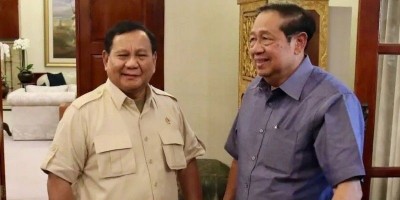Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
BELAKANGAN ini, media sosial TikTok menjadi arena baru untuk mengungkap fenomena ketimpangan sosial dengan cara yang unik dan ironis.
Lewat video-video pendek yang menyoroti hal-hal sederhana seperti perbedaan suara kipas angin dengan hujan atau keberadaan garasi motor di ruang tamu, masyarakat menggambarkan ketimpangan ekonomi dengan narasi jenaka namun menyentuh.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pengalaman keseharian masyarakat miskin dan kelas menengah bawah sering kali menjadi bahan refleksi kolektif atas kondisi ketidakadilan struktural yang telah lama berlangsung.
Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan narasi yang berbeda.
Laporan Gini Ratio Indonesia per September 2024 mencatat angka 0,381, meningkat tipis dari 0,379 pada Maret 2024.
Pemerintah menyimpulkan bahwa ketimpangan masih berada dalam kategori "sedang".
Namun, narasi ini terasa kontras dengan cerita-cerita harian netizen yang menandakan adanya krisis ketimpangan yang jauh lebih dalam dari sekadar angka statistik.
Ketimpangan: Antara Statistik dan Realitas
Data resmi sering kali menyajikan kondisi ketimpangan sebagai sesuatu yang stabil dan terkendali.
Namun, realitas sosial-ekonomi yang dialami masyarakat justru menunjukkan sebaliknya.
Perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, atau antara pusat kota dan pinggiran, memperlihatkan disparitas dalam akses terhadap air bersih, listrik, transportasi publik, hingga layanan pendidikan dan kesehatan.
Bahkan dalam satu kota yang sama, ketimpangan bisa begitu mencolok hanya dalam rentang beberapa kilometer saja.
Laporan independen dan riset akademik menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memperburuk ketimpangan dengan menambah jutaan orang ke dalam kategori rentan miskin akibat pemutusan hubungan kerja massal.
Ketika Gini Ratio hanya mencatat ketimpangan berdasarkan distribusi pengeluaran, ia gagal menangkap aspek-aspek non-moneter seperti kehilangan akses terhadap pelayanan publik atau hilangnya prospek mobilitas sosial.
Akar Masalah Underestimation Data Pemerintah
Salah satu penyebab utama mengapa data resmi sering meremehkan tingkat ketimpangan adalah keterbatasan dalam menangkap sektor informal.
Di Indonesia, sebagian besar tenaga kerja berada di sektor informal—baik sebagai pedagang kecil, buruh bangunan, pengemudi ojek daring, atau pekerja rumah tangga.
Pendapatan mereka fluktuatif, tidak tercatat secara formal, dan sangat bergantung pada permintaan harian.
Survei rumah tangga BPS yang mengandalkan wawancara formal cenderung tidak mampu menjangkau kondisi ini secara akurat.
Selain itu, pendekatan pengukuran garis kemiskinan yang bergantung pada komposisi keranjang kebutuhan dasar juga bisa memunculkan bias.
Ketika komposisi ini tidak diperbaharui dengan cepat mengikuti inflasi riil dan perubahan pola konsumsi, maka garis kemiskinan menjadi terlalu rendah dan menyebabkan angka kemiskinan atau ketimpangan tampak lebih baik daripada kenyataannya.
Ketimpangan Pasca-COVID: Dampak Kebijakan Ekonomi
Pasca-COVID, pemerintah menggelontorkan berbagai stimulus fiskal dan moneter untuk menopang perekonomian.
Namun, alokasi anggaran banyak yang menyasar korporasi besar dan proyek infrastruktur berskala nasional.
Sementara itu, kelas menengah—yang tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, namun tidak cukup kaya untuk mendapat keuntungan dari stimulus investasi—menjadi kelompok yang paling rentan.
Banyak pekerja kelas menengah yang kehilangan pekerjaan, mengalami pemotongan upah, atau bergeser ke sektor informal.
Pemerintah belum memiliki skema perlindungan sosial yang efektif bagi kelompok ini.
Di saat yang sama, mereka harus menanggung beban pajak dan iuran sosial yang relatif tinggi. Situasi ini mengikis daya beli dan mempersempit ruang mobilitas ekonomi mereka.
Ancaman terhadap Kelas Menengah dan UMKM
Kelas menengah dan pelaku UMKM menghadapi tekanan ganda: dari sisi pendapatan yang menurun akibat pandemi dan dari sisi kewajiban fiskal yang tidak disesuaikan dengan kapasitas mereka.
Alih-alih mendapatkan insentif atau pengurangan beban, banyak UMKM tetap dikenakan pajak final dan biaya operasional seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Ini menambah risiko kebangkrutan, PHK, dan bahkan kemunduran kelas sosial secara struktural.
Penurunan proporsi kelas menengah dari 21,5 persen pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024 seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah.
Ketimpangan yang tidak ditangani akan menciptakan ketidakstabilan sosial dan memperkuat oligarki ekonomi, di mana hanya segelintir orang yang menguasai kekayaan nasional.
Solusi: Redistribusi Fiskal dan Belanja Publik Berkualitas
Untuk menanggulangi ketimpangan sosial yang semakin akut, dibutuhkan kebijakan fiskal yang lebih berani dan adil.
Pertama, pemerintah perlu menerapkan pajak kekayaan (wealth tax) bagi individu dan entitas dengan kekayaan tinggi.
Pajak ini akan membantu memperbaiki distribusi aset dan menambah penerimaan negara tanpa membebani rakyat kecil.
Kedua, wacana tax amnesty sebaiknya dihentikan sementara. Program ini terbukti memberi insentif kepada para penghindar pajak tanpa menyelesaikan masalah mendasar ketidakadilan fiskal.
Justru yang dibutuhkan adalah transparansi dan penegakan hukum atas kepatuhan pajak dari kelompok berpenghasilan tinggi.
Ketiga, belanja negara harus difokuskan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.
Program padat karya, pembangunan infrastruktur desa, pelatihan keterampilan vokasional, dan pengembangan usaha lokal adalah contoh konkret dari belanja yang produktif.
Bukan justru dihamburkan untuk program yang tidak memiliki multiplier effect signifikan, seperti subsidi makan siang atau perumahan 3 juta.
Keadilan Sosial sebagai Kompas Kebijakan
Ketimpangan sosial tidak bisa lagi disembunyikan di balik statistik yang tampak stabil.
Narasi pemerintah harus disandingkan dengan realitas warga yang ditunjukkan secara gamblang di media sosial.
TikTok, dalam hal ini, bukan hanya ruang hiburan, tapi juga cermin sosial yang menunjukkan kondisi riil masyarakat bawah.
Jika pemerintah ingin menjaga stabilitas ekonomi dan sosial dalam jangka panjang, maka kebijakan yang berpihak pada rakyat banyak adalah keniscayaan.
Data harus dimaknai bukan hanya sebagai angka, tetapi sebagai panggilan untuk bertindak lebih adil, lebih merata, dan lebih manusiawi.
Ketimpangan tidak bisa dilawan dengan narasi optimisme semata.
Ia harus dihadapi dengan kebijakan berkeadilan, berpijak pada data yang jujur, dan dipandu oleh semangat bela rakyat.