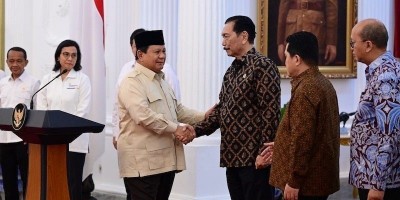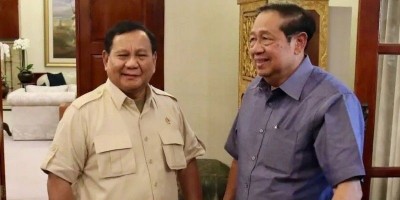Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
KETIKA Presiden Donald Trump kembali menghidupkan retorika proteksionisnya, Indonesia sekali lagi dihadapkan pada dilema geopolitik dan ekonomi yang pelik. Ancaman tarif impor hingga 32%-42% terhadap produk ekspor Indonesia bukan hanya tekanan diplomatik, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional, khususnya neraca perdagangan dan fiskal negara.
Dalam respons yang pragmatis, pemerintah Indonesia menempuh langkah kompromistis dengan menawarkan peningkatan impor produk asal Amerika Serikat, mulai dari pangan seperti gandum dan kedelai, hingga energi berupa minyak mentah dan LPG.
Langkah ini, meski secara strategis dapat meredakan tensi diplomatik dan menghindarkan Indonesia dari tarif tinggi, memiliki dampak fiskal yang tidak kecil.
Ada konsekuensi struktural yang perlu ditelaah secara kritis, mulai dari potensi penurunan penerimaan pajak, pembebanan anggaran terhadap subsidi energi, hingga risiko ketergantungan pada satu mitra dagang besar.
Dalam konteks ini, penting bagi publik dan pembuat kebijakan untuk menilai secara objektif—apakah langkah ini memang menyelamatkan, atau justru menjerumuskan kita pada jebakan ekonomi baru.
Peningkatan impor pangan dari AS menjadi langkah pertama dalam skema diplomatik ini.
Dengan target peningkatan sebesar beberapa miliar dolar AS, komoditas seperti kedelai, gandum, dan kapas dipilih karena sesuai dengan kebutuhan domestik dan tidak menimbulkan sensitivitas politik yang tinggi.
Namun demikian, impor dalam jumlah besar akan memukul pemasok tradisional seperti Australia, Kanada, dan Brasil.
Dampak langsungnya adalah Indonesia akan mengalihkan jalur pasok dan mempersempit diversifikasi perdagangan. Ini bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga geopolitik pasokan pangan yang semestinya dikelola secara hati-hati.
Fiskal Yang Mengecil
Di sisi fiskal, peningkatan impor pangan berdampak pada mekanisme perpajakan.
Untuk menarik investasi dan memberi insentif kepada importir, pemerintah telah mempertimbangkan relaksasi tarif PPN dan PPh atas produk impor asal AS.
Kebijakan ini secara jangka pendek mungkin memperlancar aliran barang, tetapi dalam jangka menengah dapat menyebabkan penurunan penerimaan negara.
Di tengah tantangan fiskal pasca-pandemi dan kebutuhan belanja publik yang masih tinggi, potensi penurunan pendapatan ini layak diwaspadai.
Pengalihan Impor Migas ke AS: Hati-Hati
Kebijakan pengalihan impor migas ke AS menjadi babak kedua dari upaya negosiasi ini.
Pemerintah menyatakan akan mengalihkan sekitar 20-30% impor minyak mentah dan LPG dari negara-negara Timur Tengah ke AS, dengan total nilai mencapai US$10 miliar.
Ini adalah langkah besar yang tidak hanya memengaruhi struktur neraca perdagangan migas, tetapi juga menyentuh aspek fiskal seperti subsidi energi dan pembangunan infrastruktur distribusi.
Karena jarak yang lebih jauh dan perbedaan kualitas produk, kemungkinan besar biaya pengadaan akan meningkat. Bila selisih ini tidak ditanggung oleh BUMN energi, maka akan masuk dalam komponen subsidi energi dari APBN.
Secara fiskal, pengalihan impor energi ini dapat memperlebar defisit jika tidak diimbangi dengan penghematan atau peningkatan penerimaan dari sektor lain.
Apalagi, kontrak jangka panjang dengan negara-negara Timur Tengah biasanya lebih stabil dan menguntungkan.
Dengan memindahkan sebagian besar pasokan ke AS, Indonesia tidak hanya mempertaruhkan kestabilan harga, tetapi juga melemahkan posisi tawar dalam negosiasi energi ke depan.
Risiko ini perlu dikaji ulang, terutama dalam konteks krisis energi global yang belum sepenuhnya mereda.
Dari sisi neraca perdagangan, peningkatan impor dari AS akan membantu mengurangi surplus perdagangan Indonesia dengan negara tersebut, yang dalam beberapa kuartal terakhir mencapai lebih dari US$4 miliar.
Hal ini memang bisa menjadi argumen kuat untuk meredam tekanan dari Washington. Namun, secara fiskal, pengurangan surplus ini tidak serta-merta menguntungkan Indonesia.
Surplus perdagangan adalah salah satu sumber utama kestabilan nilai tukar dan daya beli nasional. Mengurangi surplus tanpa diimbangi dengan ekspansi pasar ekspor lain hanya akan menggeser ketergantungan dan bukan mengurangi risiko secara struktural.
Lebih jauh, ketergantungan yang meningkat terhadap AS sebagai pemasok pangan dan energi berisiko menjerat Indonesia dalam dinamika politik luar negeri yang tak selalu sejalan dengan kepentingan nasional.
Jika kebijakan luar negeri AS berubah, atau bila Trump kehilangan kekuasaan di periode mendatang, maka strategi ini bisa menjadi bumerang.
Indonesia harus menjaga prinsip diversifikasi mitra dagang sebagai bagian dari kebijakan fiskal dan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Penting untuk dicatat bahwa strategi ini juga menyisakan dilema politik domestik.
Para pelaku industri dalam negeri, termasuk petani kedelai dan pelaku UMKM pangan, dapat terdampak oleh banjir produk impor yang lebih murah.
Pemerintah harus menyiapkan skema kompensasi, baik berupa subsidi produksi maupun pelatihan restrukturisasi usaha, untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri tidak mengorbankan rakyat kecil.
Dalam jangka panjang, upaya diplomatik untuk menghindari tarif tinggi AS perlu diimbangi dengan strategi ekonomi domestik yang kokoh.
Pemerintah harus memperkuat industrialisasi, hilirisasi, dan daya saing ekspor nasional agar tekanan eksternal seperti ini tidak lagi terlalu menentukan arah kebijakan fiskal.
Selain itu, diplomasi perdagangan harus melibatkan negosiasi yang lebih seimbang, tidak hanya menghindari hukuman tarif, tetapi juga mendapatkan akses pasar dan investasi dari AS yang lebih luas.
Dengan demikian, strategi peningkatan impor dari AS bisa menjadi alat diplomasi yang taktis, namun bukan solusi strategis jangka panjang.
Untuk menjaga kedaulatan fiskal dan ekonomi nasional, Indonesia harus berhati-hati agar tidak menukar stabilitas jangka pendek dengan ketergantungan jangka panjang.
Dalam setiap langkah kebijakan, rakyat harus menjadi pusat pertimbangan, bukan hanya angka dalam neraca perdagangan.