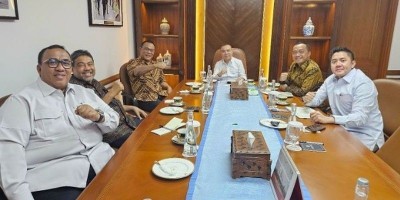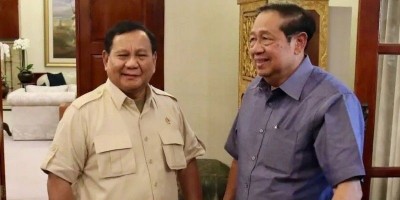Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
KETIDAKHADIRAN Presiden China Xi Jinping dalam rangkaian lawatan Asia Tenggara pada April 2025 ke Indonesia memunculkan sejumlah interpretasi strategis yang menarik untuk dikaji lebih dalam.
Banyak pihak bertanya-tanya, mengapa Indonesia—yang merupakan mitra dagang terbesar China di kawasan Asia Tenggara—tidak menjadi bagian dari agenda kunjungan tersebut.
Padahal, secara nilai perdagangan, posisi Indonesia sangat signifikan. Namun, jawaban atas pertanyaan ini justru dapat ditemukan dalam logika hubungan bilateral yang sudah mencapai tahap kematangan.
Xi Jinping memilih mengunjungi Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Ketiga negara ini memiliki posisi strategis masing-masing dalam konteks dinamika geopolitik dan ekonomi global, terutama menghadapi tekanan proteksionisme dari Amerika Serikat.
Vietnam, sebagai pengimpor terbesar produk China di ASEAN, sedang menjalin negosiasi strategis dengan AS.
Malaysia berada dalam ambiguitas arah kebijakan luar negeri, namun saat ini menunjukkan kecenderungan mendekat ke Beijing di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim. Sementara Kamboja selama ini menjadi titik tumpu investasi infrastruktur China di bawah inisiatif Belt and Road (BRI).
Lalu, di mana posisi Indonesia? Justru ketidakhadiran Xi Jinping ke Jakarta harus dibaca bukan sebagai pengabaian, melainkan sebagai simbol kepercayaan yang tinggi terhadap stabilitas dan kekuatan hubungan bilateral yang sudah mapan. Indonesia tidak lagi perlu "diyakinkan" atau "dirayu" oleh Beijing melalui simbolisme kunjungan kenegaraan.
Dalam terminologi hubungan internasional, ini mencerminkan level strategic partnership yang tidak memerlukan gestur simbolik berlebihan karena sudah didasarkan pada kesalingpahaman yang kuat.
Faktor lain yang perlu diperhitungkan adalah dinamika domestik Indonesia.
Presiden terpilih Prabowo Subianto baru saja memulai masa jabatannya, dan dalam 100 hari pertama, sudah menunjukkan komitmen diplomatik melalui kunjungan penting ke Timur Tengah dan Turki.
Prabowo juga sedang memposisikan Indonesia sebagai pemain aktif dalam isu-isu global seperti krisis Gaza dan relasi multilateral Selatan-Selatan.
Dengan agenda luar negeri yang padat, maka tidak aneh jika koordinasi waktu untuk kunjungan balasan dari pihak China menjadi sulit direalisasikan dalam waktu dekat.
Sebaliknya, justru pertemuan-pertemuan bilateral antar pejabat tinggi dan teknokrat dari kedua negara terus berlangsung intensif.
Di balik layar, kerja sama ekonomi, energi, teknologi, hingga pertahanan tetap berjalan tanpa gangguan.
Keberadaan proyek-proyek besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, investasi pada energi baru-terbarukan, serta kemitraan dalam pengembangan kawasan industri strategis, semua menunjukkan bahwa hubungan RI-China tidak mengalami friksi sedikit pun. Tidak ada penurunan intensitas atau sinyal ketegangan.
Perlu juga dicatat bahwa ketidakhadiran Xi justru menjadi momen yang menunjukkan bagaimana Beijing menghormati kedaulatan dan dinamika internal Indonesia.
Tidak ada kesan intervensi atau keinginan untuk mencuri perhatian publik Indonesia yang sedang fokus pada transisi pemerintahan. Hal ini menandakan pendekatan yang lebih dewasa dalam diplomasi China, yang mengedepankan kepercayaan sebagai fondasi kerja sama.
Jika dibandingkan, justru hubungan dagang dan politik Indonesia dengan negara-negara Barat dan Eropa tengah menghadapi tantangan yang lebih besar.
Isu deforestasi, diskriminasi produk kelapa sawit, dan ketidakadilan dalam rezim perdagangan karbon menunjukkan bahwa relasi dengan Barat tidak selalu berjalan harmonis.
Di sinilah keunggulan pendekatan China terlihat: pragmatis, tidak menggurui, dan berbasis kepentingan bersama jangka panjang.
Jadi, absennya Xi Jinping dalam kunjungan ke Indonesia bukanlah pertanda pelemahan hubungan, melainkan indikasi kedalaman relasi yang tak memerlukan validasi publik.
Indonesia sudah menjadi mitra strategis yang dipandang stabil dan kredibel dalam kaca mata Beijing.
Diplomasi Prabowo yang aktif dan fleksibel justru membuka ruang yang lebih luas untuk interaksi bilateral yang lebih substansial dan tidak semata berbasis seremoni. Ini adalah cerminan relasi dua negara besar di Asia yang saling memahami, saling membutuhkan, dan saling mempercayai.
Dengan kata lain, dalam diplomasi tingkat tinggi, ketidakhadiran pun bisa bermakna kehadiran yang penuh makna.