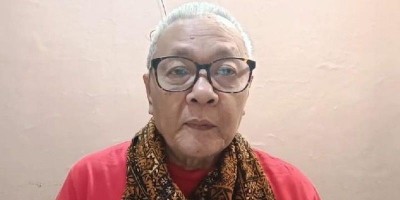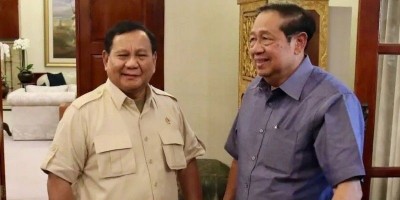Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
BELAKANGAN ini publik dibuat heboh dengan viralnya informasi bahwa petugas bea cukai dapat menerima premi atau bonus hingga 50 persen dari hasil lelang atau denda barang sitaan.
Ini diatur dalam Pasal 113D UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan diperkuat dalam beberapa peraturan menteri keuangan (PMK), termasuk yang terbaru pada tahun 2024.
Bagi sebagian besar publik, fakta ini mengagetkan karena belum pernah tersosialisasi secara terbuka.
Wajar jika kecurigaan mencuat: apakah petugas bea cukai selama ini punya motif ekonomi dalam menindak barang kiriman masyarakat? Apakah ada insentif tersembunyi yang justru mendorong pelanggaran agar terus terjadi?
Menyandarkan Insentif pada Pelanggaran: Kebijakan yang Kontraproduktif
Pada dasarnya, setiap kebijakan insentif dalam birokrasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip objektivitas, akuntabilitas, dan mendorong perilaku yang benar.
Namun ketika premi diberikan berdasarkan nilai pelanggaran—yaitu dari nilai barang yang disita, dilelang, atau didenda—maka arah kebijakannya menjadi bermasalah.
Mengapa? Karena nilai pelanggaran justru menjadi aset yang diincar, bukan kondisi yang harus dicegah.
Bayangkan seorang petugas bea cukai yang melihat peluang untuk menyita barang karena kelengkapan dokumen yang kurang, atau karena klasifikasi barang yang dapat ditafsirkan secara berbeda.
Alih-alih memberikan edukasi atau membantu proses perbaikan dokumen, ia justru bisa terdorong untuk menyita, lalu berharap premi dari nilai barang tersebut. Ini jelas menciptakan conflict of interest yang serius.
Mengapa Skema Bonus Seperti Ini Tidak Fair?
Pertama, premi yang berbasis pelanggaran menciptakan insentif untuk mempertahankan—bahkan memperbanyak—pelanggaran.
Kita tidak sedang membangun sistem yang mencegah korupsi atau pelanggaran, tapi justru mengandalkan eksistensi pelanggaran sebagai sumber penghasilan.
Dalam jangka panjang, ini akan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem kepabeanan dan memperkuat anggapan bahwa aparat bekerja demi keuntungan pribadi, bukan demi kepentingan negara.
Kedua, praktik ini bisa mendorong praktik manipulasi.
Tidak semua kasus kepabeanan bersifat hitam-putih. Banyak importir atau pengirim barang individu yang tidak paham aturan teknis bea masuk.
Alih-alih membantu, petugas bisa memperumit atau bahkan memelintir pasal untuk menjustifikasi penyitaan.
Jika premi menjadi imbalan, maka praktik over-enforcement akan makin menggila.
Ketiga, ada potensi bertentangan dengan prinsip-prinsip World Trade Organization (WTO), yang menekankan pada kemudahan perdagangan dan sistem kepabeanan yang fair dan bebas dari insentif yang bisa memicu distorsi.
Negara-negara maju umumnya memisahkan fungsi penegakan dari insentif ekonomi semacam ini karena dianggap membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Contoh: Ketika Petugas Menjadi Pemangsa, Bukan Pelindung
Bayangkan seorang mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di luar negeri dan mengirimkan buku, pakaian, atau makanan ringan ke kampung halamannya.
Jika barangnya dinilai "tidak sesuai klasifikasi" atau "melebihi batas bebas bea", maka barang tersebut bisa disita dan dilelang.
Dalam sistem yang memberikan premi atas hasil lelang, petugas punya dorongan langsung untuk menyita, bukan membantu.
Kasus lain adalah usaha kecil menengah (UKM) yang mengimpor bahan baku dari luar negeri.
Sering kali, karena keterbatasan kapasitas administratif, dokumen mereka belum sempurna. Jika aparat kepabeanan punya insentif pribadi dalam menyita barang bernilai tinggi, maka UKM bukan hanya kehilangan barang, tapi juga kepercayaan terhadap sistem.
Negara yang ingin mendorong UMKM dan investasi asing semestinya justru memperkuat layanan edukatif dan solutif, bukan represif dan insentif berorientasi hukuman.
Tidak Transparan dan Tidak Adil
Fakta bahwa aturan premi ini sudah lama ada namun tidak tersosialisasi secara luas, menunjukkan lemahnya transparansi dalam sistem.
Padahal, setiap bentuk insentif bagi aparat publik harus bisa diakses dan diketahui oleh warga negara. Ketiadaan informasi ini memperkuat kesan bahwa ada "keuntungan diam-diam" yang tidak pernah dijelaskan.
Ini bukan sekadar masalah komunikasi, tapi masalah etika dalam tata kelola pemerintahan.
Apalagi premi ini bersumber dari barang-barang yang sejatinya menjadi kerugian bagi masyarakat. Barang yang disita berarti hilangnya hak milik warga.
Jika negara kemudian membagi keuntungan dari situ, tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas dan audit publik yang kuat, maka itu bisa dikategorikan sebagai abuse of power. Dalam demokrasi, praktik semacam ini harus dikoreksi.
Perlu Evaluasi dan Dibatalkan
Maka dari itu, aturan ini harus dikaji ulang.
Insentif bisa dan perlu diberikan kepada petugas bea cukai—tetapi berdasarkan indikator kinerja yang mendorong perbaikan sistem, bukan mempertahankan pelanggaran.
Misalnya, premi bisa diberikan jika petugas berhasil membantu menyelesaikan konflik klasifikasi barang secara adil, atau ketika mereka mampu mempercepat arus barang tanpa menurunkan kualitas pengawasan.
Negara juga bisa mengalokasikan insentif berbasis capaian institusional, bukan personal.
Misalnya, kantor bea cukai yang berhasil menurunkan jumlah pelanggaran karena edukasi efektif bisa mendapat tambahan anggaran.
Ini akan menciptakan kompetisi sehat antarkantor dan memfokuskan energi pada pencegahan, bukan penindakan.
Penting: Jangan Insentifkan Pelanggaran!
Inti persoalannya bukan pada ada atau tidaknya insentif.
Tapi bagaimana insentif itu dirancang. Ketika bonus diberikan dari nilai pelanggaran, maka sistem telah salah arah. Kita tidak bisa membangun tata kelola publik yang sehat jika pelanggaran justru menjadi sumber pendapatan.
Prinsip dasar reformasi birokrasi adalah mencegah penyalahgunaan kewenangan, bukan membukakan pintunya.
Kebijakan premi bea cukai berdasarkan nilai barang sitaan harus dihentikan atau direformulasi.
Negara harus hadir sebagai pelayan dan pelindung warga, bukan pemangsa yang menanti celah dari ketidaktahuan rakyat. Jika tidak, kepercayaan terhadap sistem akan terus runtuh, dan agenda Presiden Prabowo birokrasi yang melayani akan tinggal slogan kosong semata.